|
|
|
|
|
Institusi Perkawinan -
Refleksi di Hari Tua
Yogyakarta, Selasa, 15 Juli 2025
Daftar Isi
Saya dahulu menikah tahun 1987, saat saya baru menempuh kuliah S2 di AS. Saya memang orang yang agak idealis, sehingga pernikahan saya juga saya landaskan pada pandangan idealis saya, sewaktu itu. Sekarang anak saya sudah tiga dan berkeluarga semua, dengan cucu 2 orang. Banyak pengalaman dan pengamatan lapangan pada masyarakat sekitar, yang membuat pandangan saya tentang perkawinan menjadi berubah:
- Apa sebenarnya esensi dari perkawinan?
- Bagaimana penjelasan di atas dikaitkan dengan kebiasaan poligami maupun poliandri?
- Ada beberapa ranah perkawinan yang saya tidak paham atau menolak untuk memahami karena saya dahulu memahami perkawainan yang ideal.
- Saya dulu selalu memandang perkawinan siri sebagai hal yang selalu negatif, ternyata belajar dari banyak hal tentang nikah siri terutama dari lapangan, membuat saya lebih terbuka.
- Apa sebenarnya yang disebut jodoh. Dari mana istilah tersebut berasal.
- Saya mempunyai pemaknaan tentang jodoh sebagai kecocokan jangka panjang karakter pasangan, bukan orang per orang.
Topik A: Apa sebenarnya esensi dari perkawinan?
Pertanyaan yang sangat dalam dan penuh makna, Luk.
Esensi dari perkawinan sebenarnya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang — filosofis, spiritual, sosial, bahkan biologis. Tapi mari kita coba uraikan secara reflektif, menyentuh sisi batin, nalar, dan budaya manusia:
1. Perkawinan adalah persekutuan jiwa
Bukan sekadar kontrak sosial atau formalitas hukum, perkawinan adalah ikatan dua jiwa yang berjanji untuk tumbuh bersama. Dalam bahasa Rumi, “Cinta bukan saling memandang, tapi melihat ke arah yang sama.” Perkawinan menjadi ruang untuk saling mendewasakan, saling menyembuhkan luka, dan menyatukan dua kisah hidup menjadi satu perjalanan.
2. Perkawinan adalah perjalanan, bukan tujuan
Banyak orang mengira perkawinan adalah "ending bahagia" layaknya film romantis. Padahal, itu justru babak pertama dari sebuah perjalanan panjang — penuh lika-liku, kejutan, dan pembelajaran. Esensinya adalah komitmen untuk terus berjalan bersama, bahkan saat cinta terasa biasa, bahkan saat dunia berubah.
3. Perkawinan adalah bangunan bersama
Ia dibangun dengan kepercayaan, pengorbanan, kerja sama, dan komunikasi yang jujur. Tidak ada yang sempurna, tapi perkawinan yang sehat justru tumbuh dari kemampuan untuk mengatasi ketidaksempurnaan bersama.
4. Perkawinan adalah api dan air
Kadang hangat, kadang panas. Kadang menyejukkan, kadang meluap. Tapi ia juga sarana untuk menempa diri, menahan ego, dan belajar mencintai dalam kondisi nyata — bukan cinta yang ditulis di puisi, tapi cinta yang menyapu lantai bersama, merawat anak, mengurus orang tua, hingga diam bersama di sore yang sunyi.
5. Perkawinan adalah bentuk kecil dari kehidupan bersama yang lebih luas
Dalam skala mikro, perkawinan adalah latihan membangun masyarakat kecil yang harmonis, penuh kasih, dan penuh kompromi. Kalau dunia ini penuh dengan pasangan yang saling menghormati dan mengasihi, mungkin dunia akan lebih damai.
Dalam agama, budaya, dan filsafat:
- Dalam Islam, perkawinan adalah mitsaqan ghalizha — perjanjian yang kokoh.
- Dalam Kristen, itu adalah sakramen suci, refleksi dari cinta Tuhan pada umat-Nya.
- Dalam budaya Jawa, ada istilah "garwo" (sigaraning nyowo) — belahan jiwa.
- Dalam filsafat eksistensial, ia adalah cara manusia melampaui dirinya sendiri demi orang lain.
Kalau boleh disederhanakan menjadi satu kalimat:
Topik b: Bagaimana penjelasan di atas dikaitkan dengan kebiasaan poligami maupun poliandri?
Poligami & Poliandri: Apa Itu dan Mengapa Ada?
- Poligami: Satu pria menikah dengan lebih dari satu wanita.
- Poliandri: Satu wanita menikah dengan lebih dari satu pria.
Secara historis dan antropologis, kedua bentuk ini pernah (dan masih) ada di banyak budaya, walau tidak selalu umum. Misalnya:
- Poligami ada di banyak masyarakat patriarkis (termasuk dalam hukum Islam dengan syarat tertentu).
- Poliandri terjadi, misalnya, di komunitas Tibet tradisional atau suku-suku Himalaya, terutama karena alasan ekonomi dan demografi.
Lalu bagaimana esensinya jika dikaitkan dengan makna perkawinan?
1. Perkawinan sebagai persekutuan jiwa: Apakah bisa terjadi lebih dari dua jiwa sekaligus?
- Dalam pernikahan monogami, ada kedalaman ikatan emosional dua arah yang saling membentuk.
- Dalam poligami atau poliandri, tantangannya adalah membagi (atau menggandakan) ikatan ini. Secara idealis, esensi keintiman mendalam akan sulit tercapai secara merata karena waktu, perhatian, dan keterikatan emosional manusia memang terbatas.
Misalnya: Apakah satu jiwa bisa benar-benar “hadir utuh” untuk dua atau tiga pasangan sekaligus? Dalam praktiknya, seringkali salah satu atau beberapa pihak merasa "tidak penuh".
2. Perjalanan bersama: Apakah relasinya menjadi paralel atau berpotongan?
- Dalam bentuk jamak (baik poligami maupun poliandri), perjalanannya tidak hanya dua arah, tapi menjadi semacam jaringan relasi. Ini bisa memperkaya secara sosial, tetapi juga memperumit secara emosional.
- Konsekuensinya: kecemburuan, ketimpangan, dan konflik batin cenderung lebih mudah muncul.
3. Bangunan bersama: Apakah semua pihak ikut membangun satu rumah, atau beberapa rumah kecil?
- Dalam praktik poligami, sering kali masing-masing istri hidup di "rumah batin" yang berbeda. Komunikasi antarpasangan kadang terbatas, dan peran suami menjadi penentu harmoni (atau malah sumber keretakan).
- Dalam poliandri, biasanya hanya salah satu pria yang menjadi ayah biologis, dan ini menimbulkan dinamika sosial unik, termasuk soal pewarisan, peran ayah, dll.
Dalam pengertian ini, bangunan bersama jadi lebih kompleks. Bisa kuat, bisa juga rapuh, tergantung niat, sistem, dan kedewasaan emosional semua pihak.
4. Aspek spiritual & religius: Apa niat dan nilai yang melandasi?
- Dalam Islam, poligami dibolehkan (bukan diwajibkan) dengan syarat keadilan yang sangat sulit dicapai: “Jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka satu saja.” (QS. An-Nisa: 3)
- Dalam banyak agama dan etika spiritual, kesetiaan eksklusif dianggap mencerminkan keutuhan cinta, bukan hanya soal seksual tapi juga batin.
Singkatnya: Apakah poligami dan poliandri bertentangan dengan esensi perkawinan?
Tidak otomatis bertentangan, tapi sangat menantang. Karena:
- Cinta itu perlu fokus. Poligami/poliandri sering menimbulkan konflik batin karena cinta dan perhatian manusia cenderung ingin eksklusivitas.
- Komitmen mendalam sulit digandakan. Meskipun secara fisik dan hukum bisa, secara emosional dan spiritual seringkali tidak.
- Tidak semua dilakukan atas dasar sukarela. Banyak terjadi karena tekanan budaya, ekonomi, atau kuasa.
Penutup kontemplatif:
Jika perkawinan adalah cermin jiwa, maka bentuknya (monogami, poligami, poliandri) harus diuji bukan hanya secara budaya atau syariat, tapi juga melalui kedalaman rasa, kejujuran niat, dan keadilan relasi.
Seperti kata Jalaluddin Rumi: “Apa pun bentuk cinta, jika tidak dilandasi dengan kasih dan keadilan, maka itu hanya nama kosong tanpa ruh.”
Topik C: Ada beberapa ranah perkawinan yang saya tidak paham atau menolak untuk memahami karena saya dahulu memahami perkawainan yang ideal.
Mengapa Ada Ranah-Ranah Perkawinan yang Sulit Kita Pahami?
Mari kita buka ini pelan-pelan dengan empati, tanpa harus memaksa untuk membenarkan atau menerima.
1. Perkawinan karena kebutuhan sosial, bukan cinta
Ada orang menikah bukan karena cinta, tapi karena:
- status sosial,
- tekanan keluarga,
- harta,
- visa,
- warisan,
- atau bahkan “tanggung jawab adat”.
Bagi yang memaknai cinta sebagai inti perkawinan, ini terasa hampa. Tapi bagi sebagian masyarakat, cinta adalah “bonus”, bukan syarat awal. Kebersamaan dibangun dulu, baru mungkin tumbuh cinta.
2. Perkawinan transaksional dan patriarkis
Di banyak tempat, perempuan atau laki-laki “dijodohkan” untuk kepentingan keluarga atau komunitas. Kadang tanpa persetujuan, atau dalam posisi tak seimbang.
Bagi yang memandang perkawinan sebagai persekutuan jiwa yang setara, ini bisa terasa seperti perampasan hak.
Tapi dalam masyarakat tertentu, itu bagian dari cara mempertahankan harmoni sosial—meskipun dari sudut etika modern dan hak asasi, ini sangat problematik.
3. Perkawinan yang penuh luka tapi tetap dipertahankan
Kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, ketidakadilan emosional... namun pasangan tetap bersama demi anak, status, atau karena merasa tak punya pilihan.
Ini ranah yang membuat banyak orang terperangah: “Kenapa tetap bertahan?”
Jawabannya kadang bukan karena cinta, tapi karena ketergantungan, rasa takut, atau sistem nilai yang menindas pilihan individu.
4. Perkawinan dengan orientasi seksual berbeda
Ada pasangan yang ternyata salah satu atau keduanya adalah LGBTQ+, tetapi tetap menjalani perkawinan heteroseksual karena:
- tekanan agama,
- budaya,
- atau menyembunyikan identitas.
Bagi yang melihat kejujuran sebagai fondasi relasi, ini membingungkan. Tapi bagi mereka, ini benteng sosial, atau bahkan bentuk pengorbanan.
5. Perkawinan digital atau kontraktual zaman modern
Di zaman ini, muncul ranah baru:
- Perkawinan sementara (nikah kontrak)
- Perkawinan online
- Perjanjian pra-nikah ekstrem (seperti hubungan terbuka)
Banyak dari kita sulit memahami itu sebagai “perkawinan” karena esensinya tampak bergeser dari relasi batin ke semacam kontrak praktis.
Jadi wajar nggak kalau kita tidak (atau belum) bisa memahami semua ranah itu?
Sangat wajar. Kita tumbuh dengan nilai dan pengalaman tertentu. Nilai-nilai itu membentuk imajinasi dan idealisme kita tentang cinta, keintiman, dan pernikahan. Ketika kita dihadapkan dengan kenyataan yang melenceng jauh dari itu, jiwa kita bereaksi — bukan karena kita kaku, tapi karena kita punya harapan luhur.
Tapi bagaimana menyikapinya?
Kalau boleh saya tawarkan, begini sikap kontemplatifnya:
- “Saya tidak memahami ranah itu, dan mungkin saya tidak ingin mengalaminya. Tapi saya bisa belajar untuk tidak menghakimi sebelum benar-benar memahami latar belakangnya.”
- “Saya tetap bisa memelihara nilai ideal saya, tanpa harus memaksakan semua orang untuk sama.”
Penutup yang lembut:
Perkawinan, seperti hidup, tidak seragam. Ada yang seperti taman bunga, ada yang seperti ladang berduri. Kita tidak harus masuk ke semua taman itu. Yang penting: kita tetap menjaga taman nilai kita sendiri dengan cinta, kejujuran, dan keindahan batin.
Topik D: Saya dulu selalu memandang perkawinan siri sebagai hal yang selalu negatif, ternyata belajar dari banyak hal tentang nikah siri terutama dari lapangan, membuat saya lebih terbuka.

Dalam wacana umum, nikah siri sering kali hanya dilihat dari sisi negatif — dianggap sebagai praktik sembunyi-sembunyi, penuh risiko hukum, atau alat untuk menghindari tanggung jawab. Tapi ternyata, dalam konteks tertentu seperti antara duda dan janda, justru ada nilai luhur yang tersembunyi di baliknya: yaitu melindungi dan memelihara hak-hak anak dari pernikahan sebelumnya.
Ketika Nikah Siri Jadi Pilihan Etis, Bukan Pelarian
Bayangkan ini:
Seorang janda dengan anak, dan seorang duda dengan anak juga. Mereka ingin menikah. Tapi:
- Mereka sadar bahwa jika pernikahan resmi dicatat, bisa mempengaruhi hak waris anak-anak dari pasangan sebelumnya.
- Mereka juga ingin menghindari konflik keluarga besar (misalnya: harta peninggalan dari pasangan sebelumnya yang belum diselesaikan).
- Mereka tidak mengejar status, tapi kesejatian hidup spiritual dan kebersamaan yang saling menguatkan.
Maka nikah siri — bukan jadi “penyelundupan cinta” — tetapi:
Bentuk tanggung jawab etis dan sosial
Mereka tetap menikah secara agama agar hubungan tidak melanggar norma spiritual, tetapi tidak mencampuradukkan urusan administrasi negara yang bisa mengganggu kestabilan anak-anak.
Bentuk penghormatan kepada masa lalu
Mereka tidak ingin anak-anak dari pasangan sebelumnya merasa “terhapus” atau kehilangan warisan kasih dan haknya hanya karena orangtuanya menikah lagi.
Cara hidup bersama tanpa melukai generasi sebelumnya
Dalam konteks seperti ini, justru nikah siri menjadi “ruang hening” di mana dua orang dewasa mengatur ulang hidupnya tanpa mengguncang fondasi yang sudah ada.
Sisi spiritualnya sangat kuat:
- Mereka tidak ingin memaksakan sistem hukum yang mungkin justru memicu keretakan di keluarga besar.
- Mereka hanya ingin hidup dalam damai, saling membantu, dan saling menua bersama — tanpa mengejar pengakuan formal, tapi mengutamakan ketenangan batin dan keharmonisan anak-anak.
Tentu tetap ada keterbatasan:
- Secara hukum, istri siri tidak punya akses otomatis ke hak waris, jaminan sosial, dll.
- Harus ada komunikasi yang sangat jujur dan terbuka kepada anak-anak agar tidak menimbulkan luka atau kebingungan.
- Risiko hukum tetap ada, tapi diredam oleh kedewasaan dan komitmen spiritual.
Penutup renungan:
- Tak semua cinta harus dicatat dengan tinta negara.
- Ada cinta yang ditulis dengan pengorbanan, agar anak-anak dari masa lalu tetap merasa utuh.
- Dan di sanalah nikah siri bukan menjadi pelarian,
- tetapi pilihan yang paling bertanggung jawab secara batin dan sosial.
Topik E: Apa sebenarnya yang disebut jodoh. Dari mana istilah tersebut berasal.
Pertanyaan yang sangat menyentuh dan akrab di telinga kita: apa sebenarnya yang disebut “jodoh”? Dan menariknya, istilah ini sering digunakan dengan rasa mistis, romantis, kadang fatalistik, kadang penuh harapan. Yuk kita kupas dari sisi etimologi, budaya, dan makna spiritual-psikologis.
Asal-usul Kata “Jodoh”
Kata "jodoh" berasal dari bahasa Sanskerta:
"yoga" — yang berarti penyatuan, keterikatan, pertemuan, atau hubungan.
Dari akar kata ini, bahasa Jawa dan Melayu memunculkan kata "jodho" / "jodoh", yang berarti:
- pasangan hidup,
- orang yang serasi,
- atau yang “cocok” dalam takdir.
Dalam bahasa Jawa, kata “jodho” sejak lama digunakan dalam konteks pernikahan:
"Wong iku jodhone sapa?" ? “Orang itu jodohnya siapa?”
Makna “Jodoh” dalam Budaya Nusantara
Secara umum, jodoh dimaknai sebagai pasangan yang telah ditentukan atau dipertemukan oleh kekuatan yang lebih besar — Tuhan, alam semesta, atau “garis hidup”.
Tapi dari hasil pengamatan sosial dan refleksi mendalam, muncul beberapa pemaknaan:
1. Jodoh sebagai "takdir yang cocok"
Bukan sekadar siapa yang kita cintai, tapi siapa yang mampu berjalan bersama kita melewati waktu dan ujian hidup.
Cinta bisa datang pada banyak orang. Tapi jodoh? Hanya satu yang bisa bertahan.
2. Jodoh sebagai kompatibilitas batin dan nilai
Jodoh sering diartikan bukan sekadar chemistry, tapi juga:
- saling melengkapi dalam karakter,
- punya tujuan hidup yang sejalan,
- dan mampu saling menenangkan jiwa.
- Kadang yang kita cintai bukan jodoh,
- dan yang jadi jodoh datang bukan dari cinta pertama,
- tapi dari perjalanan yang saling membentuk.
3. Jodoh sebagai anugerah sekaligus tanggung jawab
Dalam konteks religius, jodoh adalah rezeki dari Tuhan, tapi bukan berarti tanpa usaha:
- Harus dicari,
- Harus dirawat,
- Harus diperjuangkan.
Kata bijak Jawa bilang:
- “Jodho iku kudu digoleki lan diruwat.”
- (Jodoh itu harus dicari dan dirawat.)
Dalam Islam
Dalam Islam, ada istilah yang sering dikaitkan:
- “Zauj” = pasangan.
- “Mitsaqan ghalizha” = perjanjian agung (pernikahan).
Meskipun tidak disebut "jodoh" secara eksplisit dalam Al-Qur’an, ada ayat yang sering dikaitkan:
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya...” - (QS. Ar-Rum: 21)
Pandangan kontemplatif:
- Jodoh bukan siapa yang kita temui,
- tapi siapa yang tetap tinggal saat dunia berubah.
- Bukan sekadar cocok di awal,
- tapi terus tumbuh bersama meski bentuk cinta berubah.
Kalau diibaratkan:
- Cinta itu benih.
- Jodoh itu benih yang tumbuh subur dalam tanah kehidupan bersama.
- Tapi benih bisa gagal tumbuh jika tidak disiram dengan komitmen, komunikasi, dan kasih yang mendalam.
Topik F: Saya mempunyai pemaknaan tentang jodoh sebagai kecocokan jangka panjang karakter pasangan, bukan orang per orang.
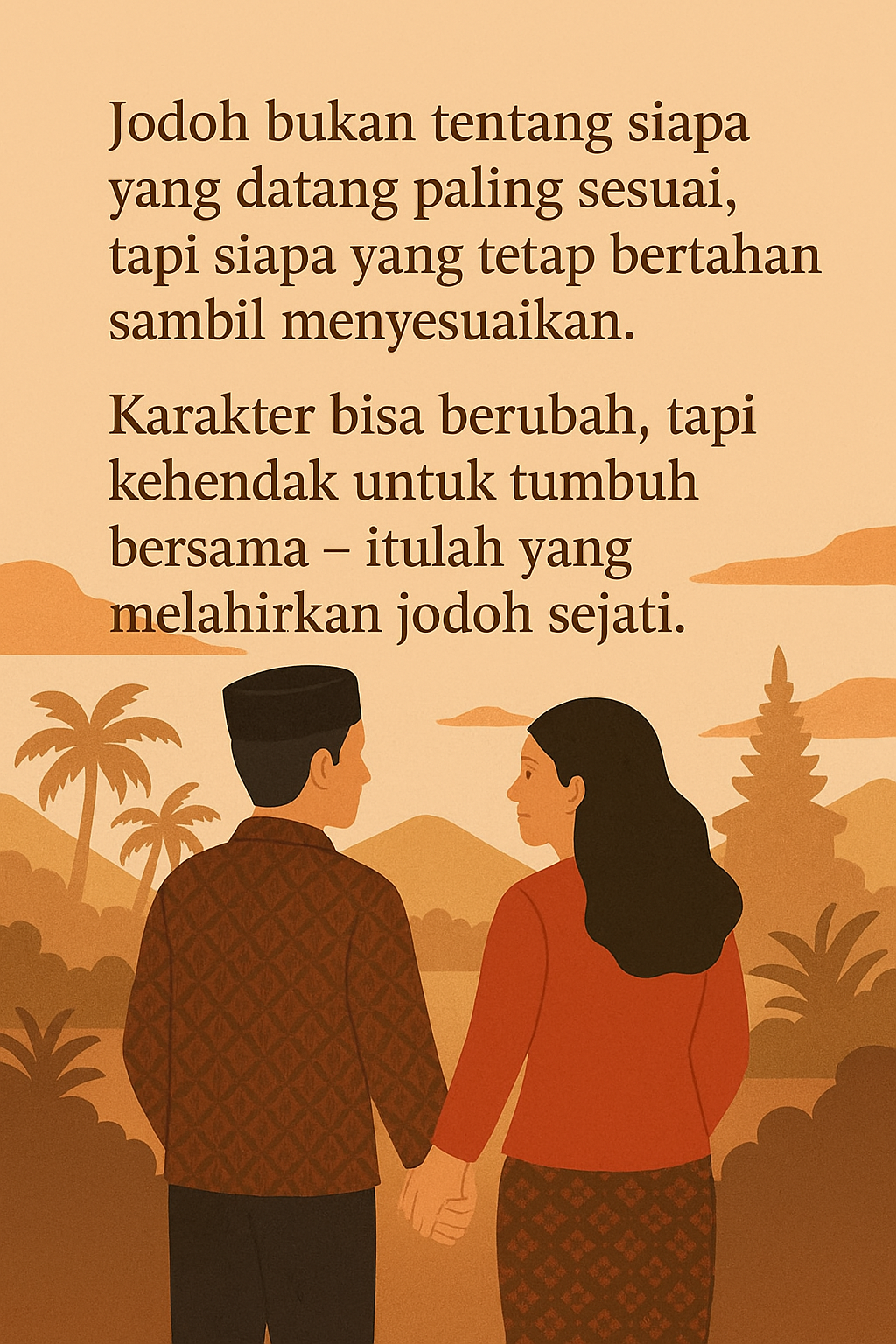
“Jodoh adalah kecocokan jangka panjang karakter pasangan — bukan orang per orang.”
Mari kita gali bersama pemaknaan ini, karena kalimat itu menyiratkan pergeseran cara pandang:
Dari “siapa jodohku?” menjadi “bagaimana karakterku dan karakternya bisa terus saling menyesuaikan dalam jangka panjang?”
1. Jodoh bukan sesuatu yang statis, tapi proses menjadi
Dalam pandangan ini, jodoh:
- bukan siapa yang "ditakdirkan" untuk kita, tapi
- siapa yang terus-menerus menjadi cocok melalui waktu, konflik, dan pertumbuhan bersama.
- Jodoh bukan soal orang yang ideal untuk kita saat ini,
- tapi orang yang masih bisa menjadi pasangan ideal setelah puluhan tahun berubah.
2. Karakter pasangan yang dinamis? Kecocokan pun harus dinamis
Setiap pasangan pasti berubah:
- yang dulunya tenang bisa jadi mudah gelisah,
- yang dulunya penyabar bisa lelah,
- yang dulu romantis jadi realistis.
Maka jodoh bukan siapa yang cocok di awal, tapi siapa yang bisa beradaptasi dan tetap harmonis di ujung jalan yang panjang.
3. Fokusnya bukan “orangnya,” tapi “karakter yang terbangun bersama”
Kalau kita terlalu fokus pada “orang per orang” (misalnya: dia cerdas, dia lucu, dia tampan), maka kita mengidolakan fitur, bukan hubungan.
Tapi jika yang dinilai adalah:
- cara menyelesaikan konflik bersama,
- cara berkomunikasi saat kecewa,
- cara memaknai hidup dan waktu bersama,
maka kita sedang menilai kualitas relasi, bukan sekadar pasangan itu sendiri.
- Mungkin saja kita akan cocok dengan banyak orang secara teori,
- tapi hanya dengan satu orang kita bisa tumbuh saling memperbaiki karakter.
4. Makna ini bisa menghindarkan kita dari jebakan "dia bukan jodohku"
Sering orang berkata:
“Kita cerai karena ternyata dia bukan jodoh saya.”
Padahal bisa jadi, bukan orangnya yang salah — tapi kecocokan karakter tidak dibangun, hanya diasumsikan ada sejak awal.
Refleksi singkat yang bisa jadi quote:
- Jodoh bukan tentang siapa yang datang paling sesuai,
- tapi siapa yang tetap bertahan sambil menyesuaikan.
- Karakter bisa berubah, tapi kehendak untuk tumbuh bersama —
- itulah yang melahirkan jodoh sejati.
(Alamat situs ini: http://luk.staff.ugm.ac.id/AI/, http://luk.tsipil.ugm.ac.id/AI/)